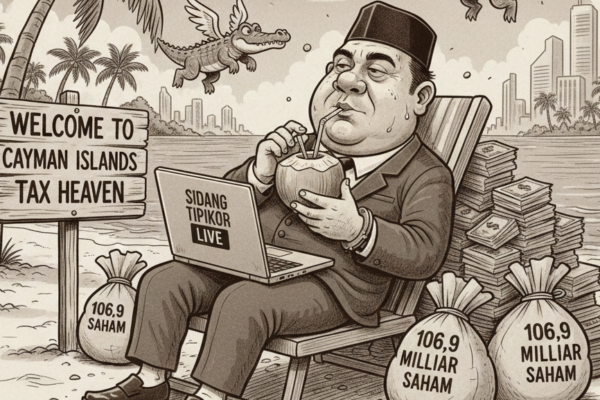Wiranatakusumah begitu serius mendukung proyek ini sampai mengirim kerabatnya tampil di layar. Sebuah langkah yang kini sulit dicari padanannya; pejabat masa kini justru lebih suka tampil di baliho ketimbang memperjuangkan film lokal.
Syuting dilakukan di gua kawasan Bukit Karang, Padalarang, sebelum daerah tersebut terkenal sebagai lokasi foto prewedding.
Film Lokal, Sambutan Lokal, Masalah Nasional
Film ini tayang perdana 31 Desember 1926 dengan iringan gamelan live yang membuat penonton bingung antara menyimak layar atau menebak akord saron.
Sayangnya, pasar di luar Sunda tidak terpikat. Penonton di Batavia dan Surabaya tampaknya memilih kisah Hollywood daripada kisah lutung yang ternyata pangeran tampan. Mereka lebih percaya monyet tetap monyet, bukan laki-laki tampan jelmaan dewi.
Akibatnya, Loetoeng Kasaroeng merugi. Film lokal pertama Hindia Belanda pun turun layar hanya seminggu, digantikan film impor yang lebih mudah dijual dan tidak membuat penonton bertanya: “Ini ceritanya apa?”
Sutradara Heuveldorp akhirnya mencari kredit obligasi untuk membuat film Eulis Atjih, yang laku keras sampai Singapura. Pendapatan film kedua inilah yang dipakai menutup kerugian film pertama sebuah pola bisnis yang tampaknya diwariskan sampai industri film Indonesia era kini.
Jejak yang Tinggal Cerita
Tak ada satu pun salinan fisik Loetoeng Kasaroeng yang bertahan. Yang tersisa hanya kliping koran lama dan ironi klasik: film yang membuka jalan perfilman nasional justru hilang tanpa jejak, sama seperti kebijakan pemerintah yang mengaku mendukung seni tapi tidak pernah benar-benar menyelamatkan arsipnya.

“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”