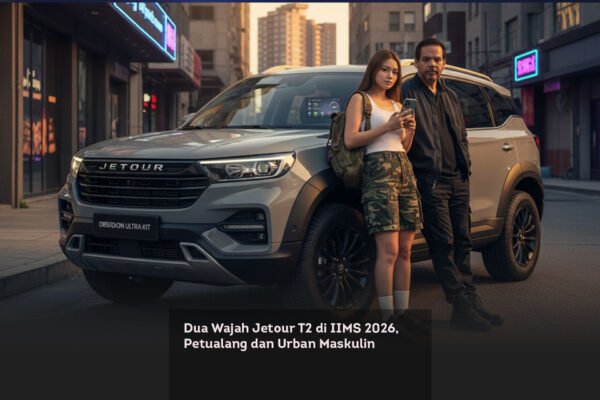“Gus Dur pernah berkata, “Tidak ada musuh dalam politik, yang ada hanya teman yang belum sepakat.” Dan kini, sejarah akhirnya sepakat dengannya.”
LOCUSONLINE, JAKARTA – Akhirnya, negara datang terlambat ke makam Gus Dur membawa gelar yang sebetulnya sudah lama disematkan rakyat: Pahlawan Nasional. Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan itu dengan khidmat. Sebuah gestur simbolik yang terasa seperti ucapan maaf bangsa pada guru yang pernah diusir dari kelasnya sendiri.
Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, wafat pada 30 Desember 2009. Sejak itu, rakyat kecil, kaum minoritas, dan mereka yang kalah dalam sistem sudah lama menabalkan namanya di hati. Hanya negara yang butuh waktu dua dekade untuk sadar bahwa ia bukan musuh, tapi mercusuar moral bangsa.
Sebelumnya, sejarah menulisnya sebagai Presiden yang dimakzulkan lewat TAP MPR Nomor II/MPR/2001 dokumen politik yang lebih banyak menyimpan rasa malu ketimbang kebenaran. Untung, pada 25 September 2024, MPR akhirnya mencabut warisan ganjil itu. Bambang Soesatyo menyebutnya “pelurusan sejarah.” Bahasa halus untuk mengatakan: “Ya, dulu kami keliru.”
Dengan hilangnya cap pemakzulan, jalan hukum menuju gelar Pahlawan Nasional terbuka. Tapi bagi publik, Gus Dur tak pernah butuh sertifikat kepahlawanan. Ia sudah menulis bab sejarahnya sendiri: membela minoritas, menertawakan kekuasaan, dan membiarkan kebijaksanaan mengalir tanpa formalitas.
Ia bukan pahlawan karena memimpin perang, tapi karena berani berdamai dengan yang berbeda. Ia menertawakan para penakut yang bersembunyi di balik ayat, dan memeluk mereka yang dikutuk atas nama iman. Ketika ia mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 dan mengakhiri diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, itu bukan keputusan politik itu pengumuman moral: Indonesia terlalu besar untuk diseragamkan.

“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”