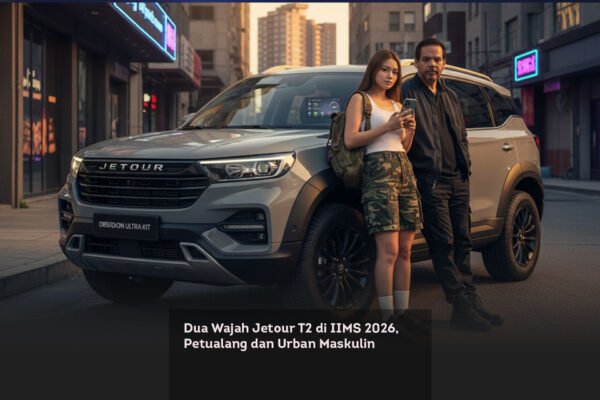Gus Dur juga tak segan membongkar simbol-simbol kekuasaan: membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang selama Orde Baru berfungsi lebih sebagai corong dan alat kontrol. Di masa itu, kejujuran politik dianggap kegilaan. Dan Gus Dur memilih menjadi gila demi warasnya bangsa.
Namun, idealisme jarang menang di ruang rapat. Koalisi runtuh, parlemen ribut, dan sejarah menulisnya jatuh. Tapi cara ia turun dari kursi presiden justru menaikkan martabatnya: tenang, tanpa dendam, tanpa kebencian. Di tengah intrik politik, ia memilih diam karena diam kadang lebih nyaring dari teriakan kekuasaan.
Kini, ketika polarisasi identitas kembali menjadi komoditas politik, penghargaan ini terasa ironis. Bangsa yang dulu menyingkirkannya kini memujanya. Tapi mungkin begitulah cara Indonesia mencintai tokohnya setelah mereka mati.
Gus Dur pernah berkata, “Tidak ada musuh dalam politik, yang ada hanya teman yang belum sepakat.” Dan kini, sejarah akhirnya sepakat dengannya.
Gelar Pahlawan Nasional mungkin sekadar kertas. Tapi maknanya: negara akhirnya belajar menjadi manusia sesuatu yang dulu sudah diajarkan Gus Dur dengan tawa dan keberanian.(Melansir berita Bandung Kompas.com*****

“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”