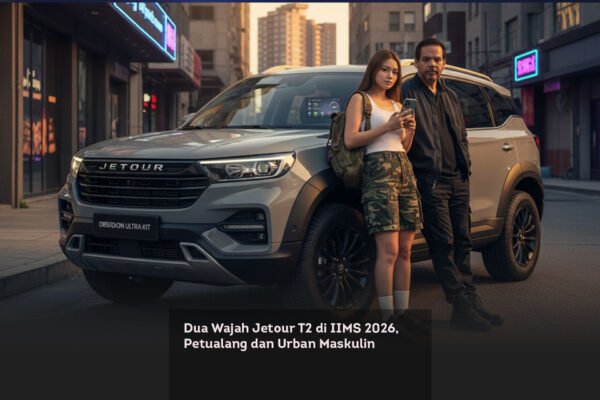LOCUSONLINE, JAKARTA — Seperti minyak yang tak pernah sampai ke permukaan, revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) terus mengendap di dasar sumur parlemen. Sudah lebih dari satu dekade sejak Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas pada 2012, namun keberadaan penggantinya, SKK Migas, tetap berstatus “sementara”—dan tampaknya nyaman dalam ketidakpastian itu. Sabtu, 19 Juli 2025
UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 seharusnya sudah diremajakan sejak lama. Tapi di gedung DPR, urgensi bukan soal waktu, melainkan siapa yang berkepentingan. Ketika publik menolak, undang-undang bisa disahkan tengah malam. Tapi ketika industri menanti, pembahasannya justru dibekukan seperti ladang tua tak tersentuh.
Dalih klasik DPR: masih banyak aturan lain yang “lebih mendesak”—revisi UU Ketenagalistrikan, UU Energi Baru dan Terbarukan, dan tentu saja, politik praktis menjelang pemilu.
SKK Migas berdiri di atas fondasi hukum darurat. Ia dibentuk setelah BP Migas dibubarkan oleh MK karena dinilai inkonstitusional. MK memerintahkan negara membentuk badan permanen melalui UU. Tapi hingga kini, negara hanya menjawab dengan diam dan penundaan.
Akibatnya, SKK Migas menjalankan mandat besar tanpa kepastian hukum. Ibarat sopir bayangan yang mengemudi kendaraan negara tanpa surat resmi.
Perdebatan tak berujung terjadi soal siapa yang seharusnya menggantikan SKK Migas. Ada yang ingin kekuasaan dikembalikan ke Pertamina seperti era Orde Baru. Pertimbangannya? Pertamina lebih fleksibel berkontrak dengan investor.

“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”