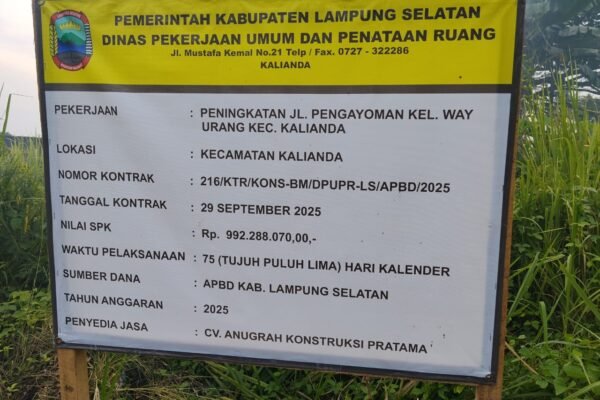Yang ironis, mahasiswa pun ikut terseret dalam dilema: dituntut menyelesaikan program “berdampak”, tapi tidak dibekali anggaran dan otoritas yang cukup untuk merealisasikan harapan masyarakat. Ketika mahasiswa gagal memenuhi ekspektasi desa, program KKN berubah jadi sekadar kunjungan singkat yang ditanggapi dingin, bahkan kadang sinis.
Bahkan, beberapa peristiwa tragis seperti mahasiswa tenggelam, pelecehan, hingga konflik lokal menandai urgensi perlunya SOP yang ketat dan refleksi menyeluruh. Namun sampai saat ini, revisi besar-besaran belum juga dilakukan. Padahal, “Law of Diminishing Marginal Utility” sedang bekerja keras: makin sering KKN dilaksanakan dengan format yang sama, makin menipis pula nilai dan dampaknya.
Kampus masih percaya mahasiswa adalah agen perubahan. Padahal desa-desa kini tak lagi gelap gulita informasi. Masyarakat tidak lagi menunggu mahasiswa membawa pencerahan—mereka butuh mitra, bukan tamu tahunan yang datang dengan program copy-paste.
Kini saatnya Kementerian, kampus, dan seluruh pemangku kepentingan meninjau ulang: apakah KKN masih layak dipertahankan, perlu dirombak, atau cukup dikenang sebagai program revolusioner masa lalu? Apalagi dengan hadirnya program baru “Kampus Berdampak”, sudah sewajarnya KKN berhenti jadi formalitas berdebu dan mulai berubah jadi aksi nyata berbasis kebutuhan, bukan nostalgia.
Karena perubahan sosial tidak datang dari mahasiswa yang turun ke desa seminggu, lalu pulang dengan laporan 40 halaman. Tapi dari sistem yang jujur menilai: mana program yang hidup, dan mana yang sekadar dipertahankan karena tak enak untuk dihentikan. (Bhegin)
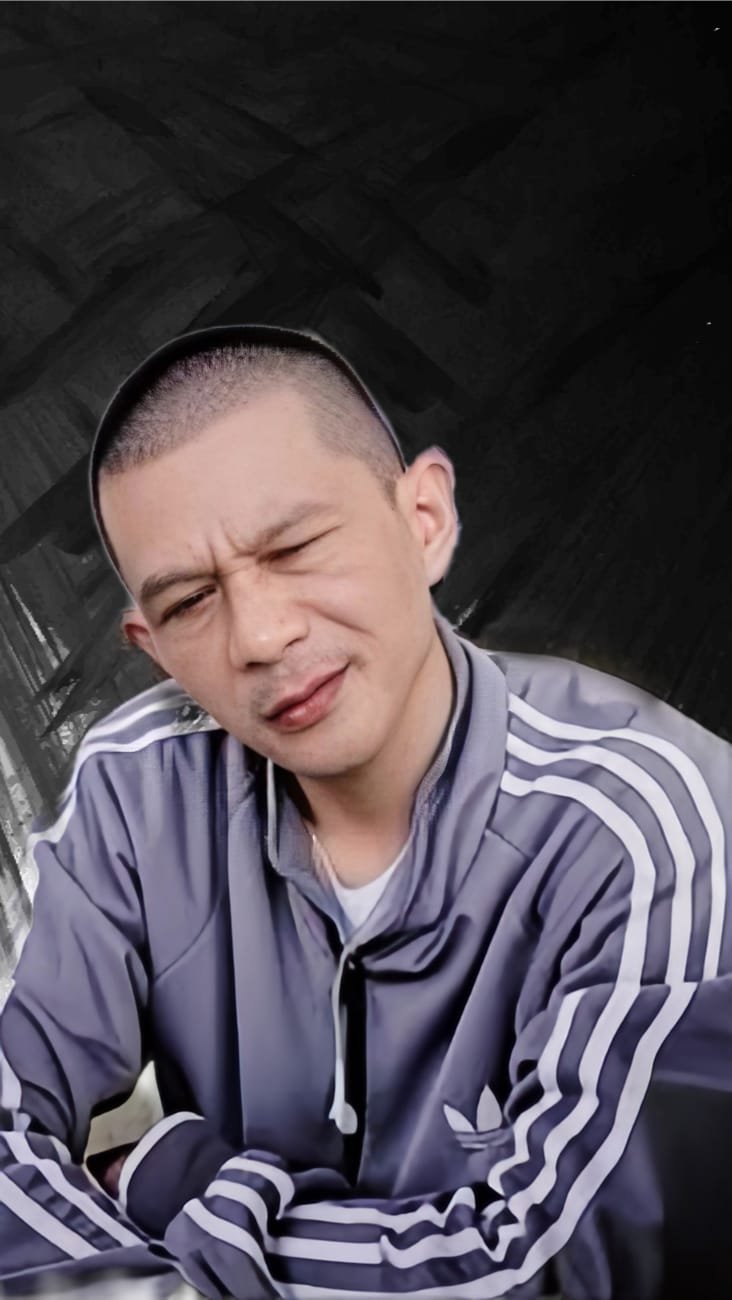
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”